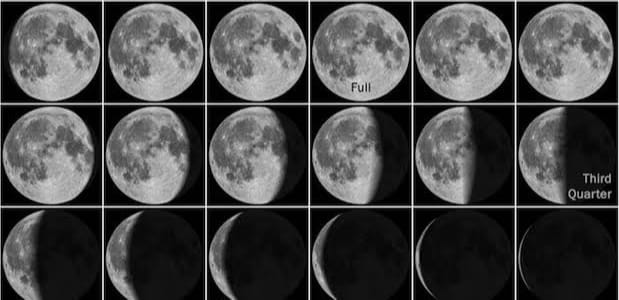Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar
Dosen FAI UMSU dan Kepala OIF UMSU
Esensi Wujudul Hilal adalah : (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Untuk menyatakan masuknya awal bulan adalah dengan terpenuhinya tiga parameter ini secara kumulatif-komprehensif, artinya apabila salah satu darinya tidak terpenuhi maka awal bulan belum dinyatakan tiba. Ini adalah cara yang digunakan Muhammadiyah sejak lama. Dengan cara ini pula ada banyak kritik yang diterima dan ditujukan kepada Muhammadiyah, kritikan itu mulai yang bersifat ilmiah-akademis hingga kritik yang penuh tendensi. Ada yang menyatakan cara Muhammadiyah ini sebagai usang dan pseudo, belakangan ada pula yang menghukumi sebagai bid’ah, bukan hasil ijtihad, mengabaikan nas sarih, dan lainnya.
Bila ditelaah, dalam konstruksinya Wujudul Hilal sesungguhnya lahir atas dasar pemikiran dan pemahaman komprehensif-interkonektif (jami’ mani’) sejumlah ayat al-Qur’an, hadis-hadis Nabi Saw, konsep fikih, dan dibantu dengan sains astronomi. Beberapa ayat itu antara lain QS. Yasin [36] ayat 39-40, QS. Ar-Rahman [55] ayat 5, QS Yunus [10] ayat 5, dan QS. Al-Baqarah [02] ayat 185. Dalam Yasin 39-40 disebutkan terdapat isyarat tiga hal penting yaitu terkait peristiwa ijtimak, pergantian siang-malam (terbenam matahari), dan ufuk (horison). Sementara Ar-Rahman 5 dan Yunus 5 menjelaskan bahwa gerak matahari dan bulan sejatinya dapat dihitung (hisab) guna menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu, diantaranya adalah perhitungan kalender.
Selanjutnya Al-Baqarah 185, kata ‘syahida’ dalam ayat ini bermakna ‘hadhara’ (berada di tempat) alias tidak musafir, sedangkan kata ‘asy-syahr’ merupakan keterangan waktu yang artinya berada di bulan Ramadan. ‘Syahida’ dalam ayat ini juga bermakna ‘ ‘alima’ (mengetahui) yang dalam konteks ayat ini maksudnya adalah mengetahui masuknya bulan Ramadan. Dengan demikian melalui ayat ini dipahami bahwa sebab syar’i wajibnya puasa adalah karena telah tiba dan diketahui masuknya bulan Ramadan. Pengetahuan dan tibanya bulan Ramadan itu dapat diperoleh dengan berbagai cara dan sarana seperti rukyat, kesaksian, istikmal, dan hisab. Artinya rukyat merupakan salah satu cara dan sarana, bukan satu-satunya.
Selain itu, ayat-ayat ini dihubungkan dengan hadis-hadis Nabi Saw, diantaranya hadis “inna ummatun ummiyyah…” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini dipahami sebagai penegasan dan alasan penggunaan rukyat yaitu keadaan umat yang belum mengenal secara luas dan mendalam tentang tulisan dan hitungan. Oleh karenanya awal bulan ketika itu ditetapkan dengan cara yang mudah dan memungkinkan yaitu rukyat, bukan hisab. Ini bermakna tatkala umat telah terbebas dari keadaan ummi maka rukyat tidak menjadi satu-satunya cara lagi, namun dapat beralih kepada hisab.
Karena itu pula dalam perkembangannya di kalangan fukaha muncul satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa sebuah ketentuan hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya kausa (al-hukm yaduru ma’a ‘illatihi wa sababihi wujudan wa ‘adaman). Atas dasar ini pula sejumlah tokoh dan ulama modern menyatakan bahwa pada dasarnya penetapan awal bulan itu adalah dengan hisab (al-ashl fi itsbat asy-syahr an yakuna bi al-hisab). Ini antara lain pendapat Qudhah, Absim dan al-Khanjari, al-Hasysyani dan Asyqifah. Berangkat dari pemahaman dan penyimpulan ini maka Muhammadiyah memilih hisab, bukan rukyat. Namun sekali lagi patut dicatat, ini adalah metode (kriteria) yang digunakan Muhammadiyah selama ini yang segera akan berganti kepada imkan rukyat global.
Prinsip hisab Muhammadiyah yang berikutnya diberi istilah dengan “Wujudul Hilal” ini juga diperkuat dengan sejumlah hadis Nabi Saw, diantaranya hadis Ibn Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan untuk mengkadarkan bilangan bulan tatkala hilal terhalang awan. Kata “faqduru lahu” dalam hadis ini secara pasti memberi tempat bagi penggunaan hisab astronomi. Adapun pendapat bahwa hadis ini mesti ditafsirkan dengan menggenapkan 30 hari (berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang lain) adalah bertentangan dengan riwayat Ibn Umar lainnya yang tidak menyebutkan 30 hari. Pandangan dan praktik Ibn Umar adalah ia memendekkan bilangan bulan 29 hari saja manakala langit berawan alias tidak menggenapkan 30 hari. Dengan demikian pernyataan menggenapkan 30 hari itu tidak autentik berasal dari Nabi Saw, melainkan interpretasi perawi yang meriwayatkan secara makna sebagai hadis. Lafal asli Nabi saw adalah sebagaimana dalam riwayat Ibn Umar yang banyak itu, yaitu “faqduru lahu” (kadarkanlah) tanpa menyebut penggenapan 30 hari.
Berdasarkan hadis ini banyak tokoh yang melegalkan hisab dalam penentuan awal bulan, yang dalam perkembangannya pengkajian hisab terus berkembang dan melahirkan banyak varian hisab sesuai pemahaman dan kemajuan pengetahuan atas gerak dan posisi benda-benda langit. Ada hisab dengan kriteria ijtimak, ada ijtimak sebelum gurub, ada ijtimak sebelum fajar, ada hisab dengan kriteria imkan rukyat, hisab kriteria wujudul hilal, hisab urfi (tabular), dan lain-lain. Semua varian kriteria hisab ini dalam sepanjang sejarah berkembang dan digunakan atau sekurang-kurangnya ada dalam diskursus para ahli dengan dinamika dan implementasinya masing-masing.
Mutharrif bin Abdillah (w. 78/697) misalnya, menyatakan apabila hilal tertutup awan maka dapat dilakukan dengan perhitungan fase-fase (posisi) bulan (An-Nawawī 6/276, Ibn Rusyd 1/2017). Lalu Ibn Qutaibah (w. 276/889), membolehkan penggunaan hisab dalam menentukan masuknya awal bulan berdasarkan pemahaman pada kata “faqduru lahu” yang diterjemahkan dengan “wa qaddarahu bi hisab al-manazil” (dan tetapkanlah dengan perhitungan posisi bulan) [An-Nawawi, t.t., 6/276].
Lalu Asy-Syirazi (w. 476/1083), menyatakan apabila hilal tertutup awan dan ada orang yang mengerti hisab dan manzilah bulan dan mengetahui bahwa bulan Ramadan telah tiba, maka ada dua pendapat, menurut Ibn Suraij orang itu wajib puasa karena telah mengetahui masuknya bulan, sedangkan pendapat lain tidak wajib (Asy-Syirazi, 1992, 2/596-597). Selanjutnya Al-Marjani (w. 1306/1889), menyatakan tidak ada larangan penentuan usia bulan Syakban dan bulan-bulan lainnya dengan hisab (Al-Marjani, 1870, 46-47).
Tampak, beberapa tokoh (ulama) ini membolehkan hisab, sedangkan hisab yang dimaksud dalam segenap pendapat mereka ini bersifat umum, tidak diketahui secara spesifik hisab dengan varian yang mana, apakah hisab ijtimak semata, ijtimak sebelum gurub, ijtimak sebelum fajar, hisab imkan rukyat, hisab urfi (tabular), atau hisab kriteria lain. Namun yang pasti mereka memahami dengan baik hisab astronomis penentuan awal bulan, juga tentunya memahami prinsip dasar hisab penentuan awal bulan yaitu ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk.
Berikutnya ada pula, bahkan cukup dominan, yang berpandangan bahwa hisab yang dimaksud adalah hisab imkan rukyat yaitu yang mempertimbangkan posisi bulan di atas ufuk dan kemungkinannya untuk teramati. Antara lain yang amat populer adalah As-Subki (w. 756/1355), ia secara tegas mendefinitifkan (qath’i) hisab dan memprobabilitaskan (zhan) rukyat, dan hisab yang ia maksud adalah hisab imkan rukyat yang tetap mengaitkannya dengan rukyat dan istikmal. Namun yang menarik As-Subki secara tegas menolak laporan hilal sementara hisab menyatakan tidak mungkin terlihat. Menurutnya, laporan (khabar) dan kesaksian (syahādah) bersifat dugaan (zhanny) sedangkan hisab bersifat definitif (qath’iy) [As-Subkī, t.t., 1/217].
Ibn Suraij (w. 306/918), menyatakan hisab perbintangan dan posisi bulan yang dengannya bulan dapat dilihat seandainya tidak ada awan, maka dalam kondisi ini awal bulan dinyatakan tiba. (Ibn Rusyd, t.t., 1/2017). Namun Ibn Suraij juga berpendapat bahwa seseorang yang mengerti hisab dan posisi bulan, dan berdasarkan itu ia yakin keesokan harinya bulan Ramadan tiba, maka wajiblah baginya berpuasa. Disini tampak Ibn Suraij mempertimbangkan hisab imkan rukyat dan hisab an sich secara sekaligus.
Selanjutnya Ibn Daqiq al-‘Id (w. 702/1302), ia memedomani hisab imkan rukyat dan menolak hisab ijtimak. Namun menurutnya rukyat faktual (ru’yah bil fi’li) tidak diharuskan untuk wajibnya memulai puasa (Ibn Daqiq al-‘Id, 1953, 2/4). Disini tampak pandangan Ibn Daqiq al-‘Id yang betapapun mempertimbangkan imkan rukyat namun ia tidak mengharuskan rukyat itu dilakukan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Wujudul Hilal adalah sebuah metode dan atau kriteria penentuan awal bulan yang didasarkan pada nas (al-Qur’an dan hadis Nabi Saw) betapapun dengan perspektif telaah dan analisis yang berbeda dari yang lainnya. Juga didukung dengan kaidah fikih dan pandangan ulama serta ditopang dengan konsep astronomi, yang tentu saja masih terdapat kekurangan dan kelemahan, terlebih dari sudut pandang pihak yang secara konsep berbeda. Ini tidak lain menjawab kritik dan tuduhan dari pihak yang teramat serius menyalahkan Muhammadiyah dengan ijtihadnya ini, yang bahkan menyatakan Wujudul Hilal dengan basis al-Qur’an, hadis, pendapat ulama, dan sainsnya ini bukan merupakan sebagai produk ijtihad. Wallahu a’lam[]